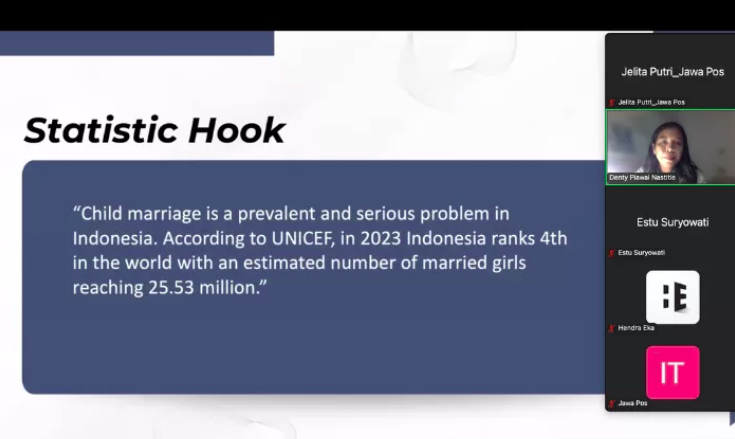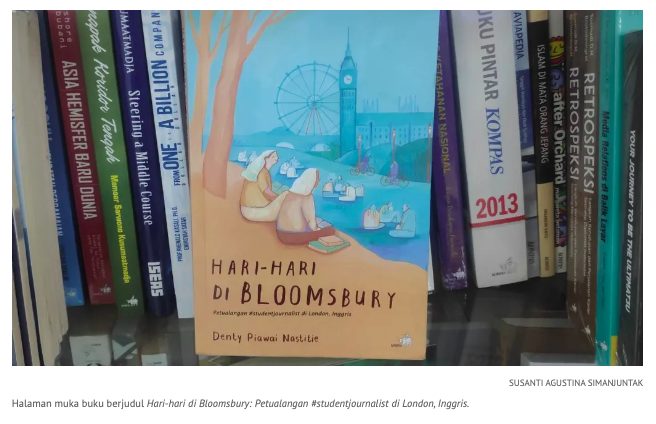Penghilangan paksa oleh negara bukan sekadar peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang telah menghapus jejak seseorang dari kehidupan, tetapi juga menghapus arah bagi keluarga yang ditinggalkan. Di balik setiap nama yang dihilangkan secara paksa, terdapat perempuan-perempuan yang terus mencari dan menunggu anggota keluarga yang hilang agar segera pulang. Mereka juga berjuang agar dapat melanjutkan kehidupan.
Nurhayati (59) masih membawa kenangan tentang ayahnya, Bachtiar, yang tak pernah pulang setelah peristiwa kerusuhan pecah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 12 September 1984. Dokumen Komnas HAM menyebutkan, tragedi Tanjung Priok 1984 sebagai salah satu luka terdalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam tragedi itu, sebanyak 79 orang menjadi korban, 55 korban luka dan 23 meninggal.
Saat terjadi, Nurhayati masih berusia 19 tahun. Malam itu, ia mendengar letusan senjata api di sekitar rumahnya. Banyak orang berlari untuk menyelamatkan diri. Rumah-rumah dibakar oleh orang tak dikenal. Keesokan harinya, Nurhayati berusaha mencari sang ayah yang sejak malam tidak terdengar kabarnya. Namun, pencariannya tak membuahkan hasil. Hingga kini, ia tak pernah lagi bertemu ayahnya.
Kehilangan sang ayah meninggalkan trauma, mengubah arah hidup, sekaligus membawa stigma berkepanjangan bagi Nurhayati dan keluarganya. Sang ibunda, yang kala itu kerap diteror dan diintai aparat tak dikenal, terpaksa menjual rumah dan melarikan diri ke Padang. ”Orang datang, tanya ’Bapak di mana’, entah siapa. Ibu jadi trauma,” kenang Nurhayati, dalam Diskusi dan Pernyataan Bersama Kongres ”Perempuan dalam Penghilangan Paksa di Indonesia” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Pengungsian itu bukan akhir dari penderitaan. Di tanah kelahiran, keluarga Nurhayati justru menghadapi stigma dan penolakan dari keluarga dan kerabat. Dalam situasi keluarga yang kehilangan figur ayah, ibunda Nurhayati harus menjadi tulang punggung sekaligus pencari keadilan dengan mencari suaminya yang hilang. Demi bertahan hidup, sang ibu harus bekerja serabutan, seperti menjadi asisten rumah tangga.
Adapun bagi Nurhayati, penghilangan paksa ayahnya berarti juga hilangnya kesempatannya untuk menjalani hidup normal. Sesaat setelah peristiwa terjadi, beasiswa pendidikan Nurhayati dicabut dan ia sulit dapat pekerjaan. Cap sebagai ”Lulusan Tanjung Priok” terus melekat seperti kutukan. ”Sudah lima kali tes kerja, tapi begitu dilihat ijazah saya dari Tanjung Priok, langsung ditolak,” katanya.
Tak hanya mengalami stigma dan diskriminasi, penghilangan paksa anggota keluarga dalam tragedi kelam juga menciptakan trauma lintas generasi dan mengakar dalam dalam ingatan kolektif keluarga. Perasaan trauma dan takut berbicara dengan orang asing, hingga sikap menutup diri jamak ditemui di antara keluarga korban. ”Dulu ngomong aja takut, kalau ngomong salah takut kami kami diculik,” ujarnya.
Adapun bagi Nur Aini (50), kehidupannya berubah total sejak 1991. Saat itu, usianya belum genap 20 tahun ketika ayahnya dihilangkan secara paksa di tengah konflik antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sejak hari itu, ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa mendadak menjadi segalanya, yakni mencari suami yang tak pernah kembali, menjadi tulang punggung keluarga bagi sembilan anak yang harus bertahan hidup, dan menerima stigma dan diskriminasi dari tetangga dan keluarga.
”Saya melihat ibu saya harus kuat di depan anak-anak, padahal batinnya tidak kuat. Dia menangis diam-diam, lalu besoknya bangun lagi untuk bekerja, mencari makan, mencari kabar ayah,” ujar Nur.

Beban berlapis itu, pelan-pelan juga berpindah ke pundak Nur. Ia kehilangan masa mudanya karena harus menggantikan peran ibu di rumah, yakni mengurus adik-adik, memastikan mereka tetap makan dan sekolah, sambil menahan rasa takut setiap kali ada di dekat rumah.
Di masa konflik, perempuan Aceh hidup dalam dilema yang nyaris tanpa ruang aman. Di satu sisi, mereka bisa dicurigai sebagai simpatisan TNI jika menolak membantu kelompok bersenjata Aceh. Di sisi lain, mereka bisa dituduh ”orang GAM” oleh aparat jika terlihat terlalu akrab dengan pihak lawan.
”Kadang hanya karena memberi sebatang rokok (kepada anggota GAM), malamnya orang itu hilang. Masyarakat sipil terjepit, tak tahu mana yang bisa dipercaya,” ujarnya.
Stigma menjadi luka tambahan yang sulit sembuh. Di masa itu, keluarga korban kerap dicap sebagai anggota Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) oleh para tetangga dan aparat. Banyak keluarga korban dikucilkan oleh para tetangga, bahkan keluarga sendiri. ”Adik saya yang masih SD diejek, ’kamu anak GPK’. Sampai sekarang trauma itu masih membekas,” ucap Nur.
Hingga kini, jumlah total kasus penghilangan paksa belum dapat dipastikan. Kontras mencatat terdapat 32.774 orang hilang dalam peristiwa 1965–1966, 1.935 orang hilang selama periode Daerah Operasi Militer di Aceh (1989–1998), dan 23 orang hilang dengan hanya 9 orang yang telah kembali pada peristiwa 1997–1998.
Penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM juga menemukan terjadinya penghilangan orang secara paksa dalam peristiwa-peristiwa lain, yaitu Penembakan Misterius 1982–1985, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989-1998, Timor Timur 1999, Wasior 2001-2002, dan Timang Gajah 2001.
Di luar peristiwa pelanggaran berat HAM, penghilangan paksa terjadi di berbagai peristiwa, termasuk Sentani 1970, peristiwa 27 Juli 1996, dan tragedi Biak Berdarah 1998. Peristiwa penghilangan paksa terus terjadi, data terbaru Kontras menerima 44 laporan orang hilang terkait demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Dalam peristiwa penghilangan paksa, perempuan keluarga korban, seperti Nurhayati dan Nur Aini kerap memikul peran berlapis, yakni merawat luka pribadi dan memperjuangkan keadilan. Selama bertahun-tahun mereka berusaha mencari anggota keluarga yang hilang sambil terus bertahan hidup. Kini, sebagian besar saksi dan korban peristiwa itu telah tiada. Hanya segelintir tersisa, termasuk Nurhayati dan Nur Aini, yang terus menjaga ingatan agar sejarah tak dikubur dalam diam.
Selama dua hari, pada Rabu dan Kamis, 15 dan 16 Oktober 2025, Kontras bersama bersama IKOHI dan AJAR dan jaringan keluarga korban penghilangan paksa menggelar serangkaian kegiatan yang berpuncak pada Kongres Perempuan dalam Penghilangan Secara Paksa. Dalam kongres itu, perempuan korban dan keluarga korban penghilangan paksa di Indonesia menyuarakan sembilan tuntutan kepada negara.
Tuntutan itu, mulai dari ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) dan penyesuaian KUHAP agar sejalan dengan prinsip HAM dan CEDAW, hingga penegakan keadilan dan perlindungan bagi korban.
Menurut Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Jane Rosalina, Kongres Perempuan mempertemukan para perempuan dari berbagai daerah dan peristiwa pelanggaran HAM berat, mulai dari Aceh, Timor Timur, tragedi 1965, hingga 1998. ”Kongres ini bertujuan menyerukan pernyataan sikap bersama terkait tuntutan perempuan dalam perlindungan dari praktik penghilangan paksa,” ujar Jane.
Ia menekankan bahwa hingga kini negara belum menuntaskan pelanggaran berat tersebut secara komprehensif, sementara para perempuan korban terus menanggung beban berlapis. Jane juga menyesalkan perspektif perempuan yang masih jarang muncul dalam penyelesaian kasus-kasus penghilangan paksa. Padahal, perempuan menjadi kelompok yang sangat terdampak.
Ia mencontohkan, banyak istri korban 1998 yang kehilangan hak-hak sipil seperti status perkawinan, waris, hingga akses ekonomi karena negara belum mengatur status hilang dalam konteks pelanggaran HAM berat.
Jane juga menyoroti berulangnya praktik penghilangan orang, termasuk kasus mahasiswa yang hilang baru-baru ini. Menurut dia, hal itu terjadi karena praktik impunitas masih mengakar. ”Negara tidak menuntut pelaku, tidak mereformasi sektor keamanan, dan tidak menjamin ketidakberulangan,” ujar Jane.
Selama tidak ada efek jera, negara akan terus terjebak dalam lingkaran kesalahan yang membuat penghilangan paksa terus berulang. Dan di balik setiap nama yang dihilangkan paksa, ada perempuan-perempuan yang bertahan, menjadi ibu, pencari nafkah, dan penjaga gerbang keadilan. (Kompas/Denty Piawai Nastitie)